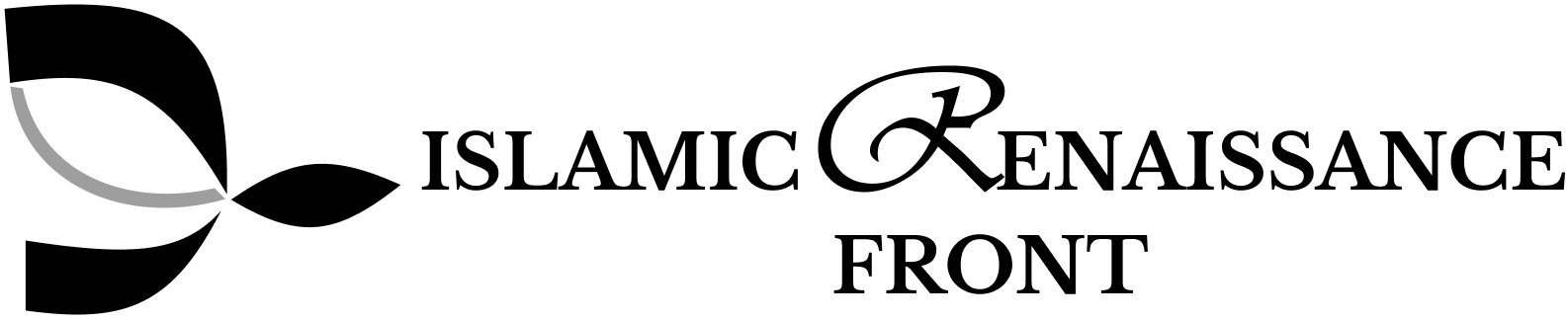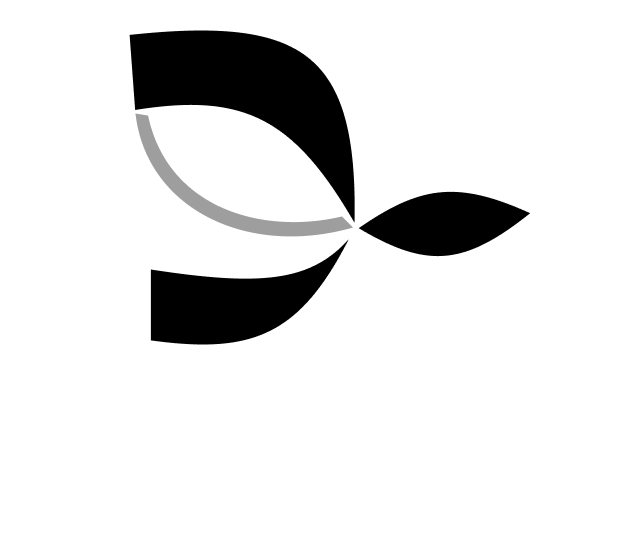Oleh: Muhammad Abdullah Darraz
Pendahuluan: Anatomi Pohon Kebajikan Ahmad Syafii Maarif
 Menyelami satu sosok pribadi yang benama Ahmad Syafii Maarif tidak dapat dilihat hanya dari satu aspek. Buya adalah seorang manusia multi-dimensional yang perlu dilihat secara utuh. Setidaknya ada beberapa perspektif fundamental yang perlu kita lihat untuk memotret siapa itu Ahmad Syafii Maarif. Prof. M. Amin Abdullah, belum lama ini dalam pidato Syafii Maarif Memmorial Lecture untuk mengenang 40 hari wafatnya Buya Syafii mengatakan, setidaknya menyebutkan ada enam aspek yang menjadi konsen seorang Buya Syafii sepanjang hidupnya, yakni keislaman, keummatan, keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan kemanusiaan. Menurut Amin Abdullah, sepanjang karir kehidupannya, Buya Syafii telah bergumul dengan tanpa lelah dengan enam elemen dasar tersebut dalam hidup beragama, bemasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[1]
Menyelami satu sosok pribadi yang benama Ahmad Syafii Maarif tidak dapat dilihat hanya dari satu aspek. Buya adalah seorang manusia multi-dimensional yang perlu dilihat secara utuh. Setidaknya ada beberapa perspektif fundamental yang perlu kita lihat untuk memotret siapa itu Ahmad Syafii Maarif. Prof. M. Amin Abdullah, belum lama ini dalam pidato Syafii Maarif Memmorial Lecture untuk mengenang 40 hari wafatnya Buya Syafii mengatakan, setidaknya menyebutkan ada enam aspek yang menjadi konsen seorang Buya Syafii sepanjang hidupnya, yakni keislaman, keummatan, keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan kemanusiaan. Menurut Amin Abdullah, sepanjang karir kehidupannya, Buya Syafii telah bergumul dengan tanpa lelah dengan enam elemen dasar tersebut dalam hidup beragama, bemasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[1]
Namun di atas enam elemen dasar yang menjadi konsen Buya Syafii itu sendiri, jika diizinkan saya ingin mencoba mendedah “anatomi konsen dan pemikiran” Buya Syafii dari tiga aspek, yakni keislaman/keimanan, keilmuan, dan amal-kemanusiaan (termasuk di dalamnya soal integritas dan moralitas). Dari sana kita akan mencoba juga melihat aspek-aspek penting sebagaimana spirit yang senantiasa dipegang oleh Buya Syafii sebagai seorang Muslim neo-modernis progresif, yang menjadikan al-Qur’an sebagai timbangan nilai dalam mengukur semua aspek dalam kehidupan ini. Maka tidak keliru kalau seandainya saya mencoba memotret sosok seorang Buya Syafii berdasarkan ayat al-Qur’an surat Ibrahim ayat 24-25.
“Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik (syajarah thayyibah), akarnya teguh, dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat”.
Ayat ini berbicara tentang kalimah thayyibah yang diumpamakan sebagai sebuah pohon kebajikan (syajarah thayyibah), yang memiliki tiga karakter: pertama, pohon tersebut memiliki akar yang kokoh yang menghujam ke dasar bumi. Dalam konteks memotret sosok Buya Syafii, maka yang dipandang sebagai akar ini adalah aspek keislaman atau keimanan dan ketauhidan yang diyakini oleh Buya yang menjadi akar penopang kehidupan Buya secara utuh dan bulat. Satu hal yang seringkali luput dibicarakan oleh publik ketika berbicara tentang pemikiran Buya. Karena ada sebagian orang yang menyebutkan Buya adalah tokoh liberal yang telah melepaskan agama/keimanan dalam kehidupannya.
Kedua, pohon tersebut memiliki dahan yang kuat dan rantingnya tinggi menjulang ke langit. Perumpamaan ini terkait dengan konsen keilmuan Buya. Sebagaimana kita ketahui Buya adalah seorang Cendekiawan dan Intelektual Publik yang selama ini memiliki konsen terhadap realitas sosial umat dan bangsa. Ia mendedikasikan dirinya sebagai corong bagi kepentingan masyarakat luas dengan berbagai tulisan, karya dan ilmu-ilmu yang menjadi minat utamanya. Ia bukan seorang intelektual di menara gading. Tapi konsen keilmuannya dipakai untuk menjadi alat melakukan perubahan sosial, menyadarkan masyarakat, dan mengkritisi pemerintah/Negara yang dianggap belum mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Sebagai peminat sejarah, ia memberikan analisis yang mendalam dan kritis tehadap jalannya sejarah umat Islam sejak periode-periode awal kehadiran Islam hingga pada masa kontemporer, sehingga umat dapat “siuman” dari berbagai kejumudan, keterpurukan, dan kemunduran yang terjadi dan apa yang menjadi akar penyebab keterpurukan umat Islam pada umumnya di dunia dewasa ini.
Ketiga, pohon tersebut menghasilkan buah yang tak bermusim. Buahnya selalu ada memberikan kemanfaatan bagi siapapun yang ingin memetiknya. Buya seperti pohon besar dengan daun dan buah yang lebat menjadi tempat berteduh bagi siapa saja dari berbagai latarbelakang yang berbeda, baik agama, ras, suku, budaya dan sub-kultur lainnya. Buah itu berbentuk kecintaan Buya pada bangsa dan negeri ini, juga sikap Buya yang sangat toleran tehadap realitas perbedaan, sangat ramah dan memperhatikan terhadap kelompok miskin dan tepinggirkan, kelompok minoritas yang tertindas, juga integritas serta moralitas yang berada di atas rata-rata penduduk negeri ini. Dalam hal kemanusiaan ini, Buya juga senantiasa memperjuangkan keadilan sosial, karena kemanusiaan tanpa keadilan sosial, hanya menjadi menciptakan kerapuhan bagi bangunan kemanusiaan itu sendiri.
Keimanan yang Teruji
 Buya Syafii adalah seorang Muslim sejati. Seorang yang memiliki keimanan yang kokoh. Inilah yang jika diumpamakan dengan pohon kebajikan di atas, ia memiliki akar yang kokoh. Keimanan seorang Buya adalah sebuah akar menghujam di dasar hatinya. Keimanan yang telah teruji. Di sepanjang separuh hidupnya, Buya mengalami betul ujian-ujian besar dalam kehidupannya. Ujian-ujian yang telah menguji keimanannya. Tidak kurang sepanjang empat puluh tahun pertama kehidupannya, Buya berkarib sangat intim dengan penderitaan, kemiskinan, kesengsaraan dan kehilangan yang beliau lalui bersama istri tercinta beliau, Bu Lip (Khalifah).
Buya Syafii adalah seorang Muslim sejati. Seorang yang memiliki keimanan yang kokoh. Inilah yang jika diumpamakan dengan pohon kebajikan di atas, ia memiliki akar yang kokoh. Keimanan seorang Buya adalah sebuah akar menghujam di dasar hatinya. Keimanan yang telah teruji. Di sepanjang separuh hidupnya, Buya mengalami betul ujian-ujian besar dalam kehidupannya. Ujian-ujian yang telah menguji keimanannya. Tidak kurang sepanjang empat puluh tahun pertama kehidupannya, Buya berkarib sangat intim dengan penderitaan, kemiskinan, kesengsaraan dan kehilangan yang beliau lalui bersama istri tercinta beliau, Bu Lip (Khalifah).
Sejak usianya masih sangat-sangat dini, ia sudah ditinggalkan oleh Ibunya, Fathia. Tepatnya pada saat usianya masih 18 bulan, ibundanya yang telah melahirkannya wafat pada tahun 1937. Buya menceritakan dalam sebuah tulisan Resonansi Republika “Demikianlah saat saya berusia 18 bulan pada tahun 1937, ibu wafat, sehingga bagaimana wajah dan perawakannya tak terbayangkan sama sekali.”[2]
Setelah ditinggal ibunya pada usia 2 tahun kurang, Buya kecil diasuh oleh keluarga paman dan bibinya yang merupakan adik kandung ayahnya, selama tidak kurang 16 tahun. Sepanjang usia tersebut buyamengenyam Pendidikan di sekolah rakyat dan sekolah Muhammadiyah. Sekolah dasarnya dihabiskan disekolah rakyat dan sekolah ibtidaiyah Muhammadiyah, dan smpnya di pesantren Mualimin Muhammadiyah Lintau yang berjarak 45 km dari kampung halamannya. Lalu di usia 18 tahun Buya merantau ke Yogyakarta untuk melanjutkan sekolah di pesantren Muallimin Yogya dengan berbagai keterbatasan yang menghinggapinya. Dua tahun ketika berada di Yogya, ayahnya pergi untuk selamanya di saat usia Buya baru beranjak 20 tahun. Karena tidak ada biaya, ia tidak bisa pulang kampung untuk melakukan penghormatan terakhir dan menghadiri pemakaman ayahnya.
Dalam situasi sebagai anak rantau yang penuh dengan keterbatasan, Buya dikirim oleh Muallimin Yogya sebagai anak panah Muhammadiyah untuk mengabdi di sebuah desa bernama Pohgading di Pulau Lombok. Setelah setahun mengabdi di Pohgading, Buya kembali ke Jawa untuk melanjutkan studi tingkat univesitas. Akhirnya setelah melalui kelas sekolah pendahuluan, Buya diterima di Universitas Cokroaminoto dan belajar selama 6 tahun antara 1957-1964.
Dalam pengakuannya sebagai seorang yang hidup dalam kemiskinan, Buya mengatakan, “suasana hidup miskin adalah pakaianku sehari-hari selama bertahun-tahun. Gontai dan tertatih langkah ini untuk berumah tangga pada waktu itu sering benar dibayangi oleh situasi yang serba kekurangan itu. Guncang batinku juga tidak terlepas dari lingkaran situasi yang masih serba melilit itu”.
Setelah Buya berumahtangga, ujian kehidupan datang silih berganti. Ketika keluarga kecil ini dikaruniai seorang anak bernama Salman, kehidupan keluarga ini dililit oleh tekanan dan himpitan ekonomi, sehingga anak yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi menderita kurang gizi. Anak pertama Buya ini tidak dapat tumbuh dengan normal. Di saat anak seusianya sudah dapat berjalan, Salmantidak dapat melakukannya. Di saat masa-masa kritis ini, Ibu Lip dan Salman harus terpisah dari Buya untuk kembali ke Padang agar Salman dapat diurus di kampung halaman oleh keluarga istrinya Buya. Hingga kabar duka itu tiba, Salman yang lahir dalam keadaan sakit-sakitan tidak dapat bertahan hidup. Pada usia kurang dari 20 bulan, anak pertama ini akhirnya meninggal dunia, dipanggil oleh Allah swt. Buya yang sedang berada di rantau di Yogyakarta, baru bisa menjenguk istri dan makam anaknya 6 hari kemudian. Ada hal yang menyayat hati ketika membaca kesaksian Buya tentang hal ini:
“.. Salman berpisah denganku dan kembali ke Padang karena tekanan dan himpitan ekonomi rumah tangga yang gagal kuatasi. Karena kondisi labil semacam inilah Lip dan Salman harus begabung dengan keluarganya di Padang.”[3]
Setelah peristiwa meninggalnya anak pertama Buya, berbagai ujian terus menimpa Buya hingga sepanjang delapan tahun perjalanan hidup Buya bersama keluarga. Termasuk kematian anak kedua beliau yang bernama Ikhwan, ketika beliau sedang mengambil studi master Sejarah di Amerika Serikat, tepatnya di kampus Northern Illinois University pada tahun 1973. Tidak kurang sampai usia Buya 40 tahun, ujian-ujian berupa penderitaan, kesengsaraan, dan kehilangan itu terus datang bertubi-tubi.
Inilah saya kira yang menjadi alasan kuat mengapa keimanan Buya semakin hari semakin kokoh. Keimanan yang telah teruji. Tapi ketika kehidupan Buya bersama keluarga mulai merangkak naik, ujian kenikmatan dan kehidupan serba berkecukupan juga dapat Buya lalui secara baik dan konsisten. Buya tetap menjalani laku hidup sederhana. Tidak merasa menjadi orang-kaya baru yang mengubah pola dan gaya hidupnya menjadi seseorang yang berbeda. Buya tetap menjadi seorang yang tidak berpola hidup berlebihan. Karena Buya sangat paham agama, dan sangat menyadari realitas mayoritas masyarakat Indonesia masih terhimpitdalam kemiskinan, dan serba kekurangan. Maka di sinilah Buya menampakkan keimanan yang empatik. Keimanan yang tidak hanya bersifat vertikal, namun juga keimanan itu berbuah pada konsern dan kegelisahan terhadap realitas sosial yang patut ia perhatikan.
Maka bukan hanya keimanan yang kuat yang menghujam dalam dirinya, juga keimanan yang senantiasa dibaluti oleh rasa syukur kepada Tuhan atas berbagai karunia yang ia terima seberapapun sulit keadaan yang ia hadapi. Dalam hal rasa syukur ini, Buya menulis,
“Hanya Engkaulah Ya Allah yang memahami betul betapa dalam rasa syukurku kepadamu. Arwah ayah-bundaku tentu akan tersenyum menyaksikan anak bungsunya belajar sampai jauh ke Barat. Tanpa bimbingan-Mu ya Allah, anak piatu yang digendong ayahnya ke tepi Batang Sumpur setelah ibunya wafat boleh jadi tidak akan ke mana-mana. Paling-paling jadi pedagang kecil tingkat desa ataukecamatan, lalu beranak pinak di sekitar itu. Oleh sebab itu, jangan biarkan aku lengah dalam bersyukur kepada-Mu. Jangan Engkau biarkan aku mati rasa setelah bergunung nikmat-Mu dilimpahkan kepadaku sekeluarga, nikmat-Mu yang tanpa putus, tanpa batas”.[4]
Keimanan Buya Syafii bukanlah keimanan yang egoistik, namun lebih jauh keimanannya menjadi dasar bagi sikap yang ramah dan humanis bagi realitas perbedaan yang ada di dunia ini. Keimanan tentang kebenaran Islam tidak lantas meluruhkan sikap respek dan rasa hormatnya terhadap pemeluk agama lain yang berbeda. Keimanan Buya benar-benar diresapi dalam batinnya baik dalam laku kehidupan sehari-hari, dalam ritual ibadah, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 Namun demikian, Buya adalah seorang yang senantiasa mempertanyakan keimanannya, dalam artian sejauh mana keimanan itu memiliki dampak positif bagi kehidupan ini? Apa bedanya orang-orang pemegang “sertifikat” keimanan dengan orang yang tidak dalam perlombaan membangun peradaban ini? Dalam sebuah tulisan, Buya mempertanyakan lebih jauh bagaimana agar keimanan dan aqidah umat ini menjadi lebih efektif, menjadi kekuatan dan memiliki dampak sosial. Dengan mengutip pandangan Malek Bennabi (1905-1973), Buya menyatakan bahwa masalah yang kita hadapi bukanlah bagaimana membuktikan (an-nubarhina) tentang eksistensi Tuhan kepada kaum Muslim, tetapi bagaimana kita membuat kaum Muslim merasakan eksistensi-Nya serta mengisi jiwanya melalui refleksi tentang-Nya sebagai sumber energi.[5] Bagi Bennabi sebagaimana diamini oleh Buya Syafii, iman adalah sumber energi untuk mengubah realitas sosial ke tingkat yang lebih baik dan lebih sempurna. Oleh karenanya iman akan menuntut pada dinamisme dan kreativitas seseorang secara terus menerus untuk mengubah arah dan jalannya sejarah.
Namun demikian, Buya adalah seorang yang senantiasa mempertanyakan keimanannya, dalam artian sejauh mana keimanan itu memiliki dampak positif bagi kehidupan ini? Apa bedanya orang-orang pemegang “sertifikat” keimanan dengan orang yang tidak dalam perlombaan membangun peradaban ini? Dalam sebuah tulisan, Buya mempertanyakan lebih jauh bagaimana agar keimanan dan aqidah umat ini menjadi lebih efektif, menjadi kekuatan dan memiliki dampak sosial. Dengan mengutip pandangan Malek Bennabi (1905-1973), Buya menyatakan bahwa masalah yang kita hadapi bukanlah bagaimana membuktikan (an-nubarhina) tentang eksistensi Tuhan kepada kaum Muslim, tetapi bagaimana kita membuat kaum Muslim merasakan eksistensi-Nya serta mengisi jiwanya melalui refleksi tentang-Nya sebagai sumber energi.[5] Bagi Bennabi sebagaimana diamini oleh Buya Syafii, iman adalah sumber energi untuk mengubah realitas sosial ke tingkat yang lebih baik dan lebih sempurna. Oleh karenanya iman akan menuntut pada dinamisme dan kreativitas seseorang secara terus menerus untuk mengubah arah dan jalannya sejarah.
Dalam soal keimanan ini, kita juga bisa menangkap secara jelas bagaimana keimanan seorang Buya Syafii pada al-Qur’an. Bagi Buya, tidak ada keraguan secara eksistensial tentang keberadaan al-Qur’an sebagai kitab pedoman dan petunjuk bagi kehidupan. Buya juga memposisikan al-Qur’an bukan hanya sekedar petunjuk dalam persolan keagamaan, namun lebih jauh Buya menjadikan al-Qur’an sebagai pedoman dalam mencarikan persoalan kehidupan yang dihadapi, dengan catatan al-Qur’an diajak dialog dengan menggunakan aqlun shahih wa qalbun salim.
“Bagiku, Al-Qur’an adalah rujukan terakhir dan tertinggi dalam merumuskan sikap hidup beragama. Inilah aku setelah dewasa, setelah belajar al-Qur’an daripada Fazlur Rahman selama beberapa tahundi Chicago, tempat pendidikanku yang terakhir sekalipun dalam usia yang hampir mendekati setengah abad karena memang demikianlah jalan hidup yang harus dilalui”[6]
Pembacaan dan penafsiran terhadap al-Qur’an bagi Buya Syafii harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang lebih kreatif dan dinamis, agar petunjuknya dapat benar-benar merespon persoalan kemanusiaan kekinian[7] dan syukur-syukur dapat membentuk tatanan peradaban baru yang lebih ideal yang dapat memayungi kehidupan harmonis-damai kemanusiaan universal. Dalam hal ini Buya menyampaikan,
“Peradaban Islam tidak boleh dibiarkan seperti “kerakap di atas batu, mati tidak, hidup pun enggan. Harus ada keberanian untuk melakukan terobosan dengan berpijak atas dalil-dalil agama yang dipahami secara benar dan cerdas, tekstual sekaligus kontekstual.”[8]
Soal pendekatan yang lebih dinamis dan kreatif dalam memahami ayat-ayat al- Qur’an, Buya menegaskan,
“Penafsiran Islam klasik jangan dijadikan “berhala”, sehingga hilang keberanian untuk menafsirkan Islam dengan cara baru, segar, dan bertanggungjawab. Tafsiran baru ini harus benar dalam perspektif ilmu, tetapi tetap berada dalam parameter iman yang tulus”
Buya percaya – sebagaimana diyakini pula oleh gurunya Fazlur Rahman, bahwa realitas umat Islam yang jauh dari cita-cita ideal al-Qur’an bukan karena kesalahan al-Quran itu sendiri yang bagi sebagian orang problematis dan dianggap sukar untuk diterjemahkan dan dimplementasikan dalam kehidupan di bumi yang empiris ini. Kekeliruan itu terjadi ketika umat ini hidup dan menjalankan misi kesejarahannya tanpa panduan al-Qur’an yang dipahami secara benar. Dalam bukunya, Buya mengutip pendapat gurunya, “We live in a different kind of Islam, not in a Qur’anic Islam”. Kira-kira kalau dipahami terjemahannya adalah “Saat ini kita hidup dalam corak Islam yang lain, bukan dalam Islam yang Qur’ani”.[9]
Rupanya baik Buya maupun Rahman sama-sama menyadari bahwa Islam yang kita jalankan saat ini tidak lagi merujuk pada sebuah Islam yang didasarkan pada konsep al-Qur’an yang jenuin dan orisinal. Dalam penjelasan selanjutnya Buya menyatakan, bahwa saat ini al-Qur’an tidak lagi dipahami secara benar dan cerdas. Hal ini yang membuat umat Islam menjadi umat yang tertindas, bodoh, dan miskin. Islam yang dijalankan tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur’an. Bahkan dalam sebuah ceramah, untuk memperkuat pandangannya ini, Buya mengutip sebuah ayat al-Qur’an yang cukup relevan untuk membaca kelakuan umat pengikut Nabi Muhammad ini dalam memperlakukan al-Qur’an. Allah berfirman: “Berkatalah Rasul: YaTuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan al-Qur’an itu sesuatu yang tidak diacuhkan (mahjura)” (Q.S. al-Furqan: 30)
Bahkan suatu saat dalam pertemuan terbatas yang menghadirkan tidak lebih dari 10 orang cendekiawan Muslim Top Indonesia[10], Buya membela al-Qur’an yang menjadi pedoman hidupnya itu ketika seorang sarjana Muslim memberikan “tantangan” dengan mengatakan, bahwa al-Qur’an ini merupakan kitab suci yang problematis, banyak ayat-ayat di dalamnya yang memang mengajak pada kekerasan. Rupanya seorang intelektual didikan barat yang sama-sama pernah mengenyam pendidikan di kampus tempat Buya berkuliah ini (University of Chicago) meyakini bahwa bukan hanya penafsiran para mufassir yang problematis, tetapi al-Qur’an itu sendiri yang problematis dengan keberadaan beberapa ayatnya yang cenderung pro tehadap kekerasan. Pada saat itu Buya lantas menyanggah pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa al-Qur’an sama sekali tidak bepretensi demikian. Dalam keyakinan Buya, al-Qur’an adalah kitab suci yang penuh kebenaran, tidak mengandung problem sebagaimana diutarakan oleh intelektual tersebut. Tafsiran yang cenderung pro pada kekerasan lah yang menjadi biang kerok sehingga seolah al-Qur’an dipersepsikan orang menjadi problematis. Dalam hal ini posisi intelektual Buya jelas membela al-Qur’an dan menyalahkan umat atau pembaca atau penafsir yang gagal mengambil inti makna dari pesan-pesan yang terkandung dalam al-Qur’an.
Keilmuan: Membaca Sejarah dan Masa Depan Politik Umat Islam secara kritikal
 Dalam hal keilmuan Buya adalah seorang peminat dan pembaca sejarah dengan sebuah “misi tertentu”[11]. Oleh karena itu, ketika membaca narasi sejarah umat Islam, Buya mencoba membacanya denganpembacaan yang sangat kritis. Buya seolah ingin mengabarkan pada publik bahwa Islam sebagai agama yang diyakini dan dianutnya, belum berhasil memberikan persembahan terbaik bagi dunia dewasa ini. Dan menjadi tugas dan tanggungjawab umat Islam untuk mewujudkan sesuatu bagi peradaban dunia. Ada juga kerisauan batin yang terus menyala dalam diri Buya tentang Indonesia, tanah air yang sangat ia cintai dan identitas keindonesiaan yang belum tuntas, di mana di dalamnya belum berhasil mewujudkan janji-janji kemerdekaan yang pernah diucapkan oleh para pemimpin sejak puluhan tahun yang lalu.
Dalam hal keilmuan Buya adalah seorang peminat dan pembaca sejarah dengan sebuah “misi tertentu”[11]. Oleh karena itu, ketika membaca narasi sejarah umat Islam, Buya mencoba membacanya denganpembacaan yang sangat kritis. Buya seolah ingin mengabarkan pada publik bahwa Islam sebagai agama yang diyakini dan dianutnya, belum berhasil memberikan persembahan terbaik bagi dunia dewasa ini. Dan menjadi tugas dan tanggungjawab umat Islam untuk mewujudkan sesuatu bagi peradaban dunia. Ada juga kerisauan batin yang terus menyala dalam diri Buya tentang Indonesia, tanah air yang sangat ia cintai dan identitas keindonesiaan yang belum tuntas, di mana di dalamnya belum berhasil mewujudkan janji-janji kemerdekaan yang pernah diucapkan oleh para pemimpin sejak puluhan tahun yang lalu.
Pertama terkait Islam termasuk di dalamnya Politik Islam yang semakin hari semakin mengalami disorientasi, dan bahkan dalam pandangan Buya menuju pada tubir kebangkrutan, terutama bila dilihat dari segi moralitas dan memakai al-Qur’an sebagai alat ukur nilainya.
Dalam konteks ini, Buya semakin merisaukan wajah Islam yang semakin tidak ideal, yang jauh dari spirit dan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an. Karena seharusnya Islam yang hadir dan hidup di bumi adalah Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu memberi solusi tehadap masalah-maslah besar baik dalamkonteks kebangsaan, kenegaraan, maupun dalam milieu yang lebih luas yakni fora dunia[12]. Atau dalam bahasa rumusan al-Qur’an, adalah Islam yang menjadi rahmat bagi semesta (rahmatan li al-‘alamin). Islam yang dibayangkan oleh Buya adalah Islam yang memberikan keadilan, kenyamanan, keamanan, dan perlindungan kepada semua orang, tanpa diskriminasi, apapun agama yang diikutinya atau tidak diikutinya. Namun dalam kenyataannya wujud Islam yang semacam itu masih jauh dari harapan dan realita. Ini yang menjadi kegalauan dan kerisauan Buya selama ini.
Dalam hal kerisauannya tentang masa depan Islam yang tengah mengalami kemerosotan ini dan berada di burit peradaban, pandangan kritis Buya terasa sangat tajam menelusur secara historis ke akarnya yang terdalam. Dalam memandang masa depan dunia Islam, Buya menarik busur analisisnya secara sangat jauhke berbagai peristiwa historis umat Islam terutama pada periode-periode awal pembentukan umat ini, terutama pada berbagai peristiwa mencengangkan pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bagi Buya, periode tesebut menjadi masa-masa yang sangat menentukan nasib perjalanan umat Islam selanjutnya, dan bahkan ekses negatifnya dirasakan hingga saat ini.
Dalam banyak tulisan, sebagai seorang peminat sejarah, Buya menemukan bahwa asal mula dan biang kerok kemunduran Islam bisa dilihat dari akar konflik dan pertikaian yang terjadi duapuluh empat (24) tahun setelah Rasul wafat. Yakni pertikaian politik setelah terbunuhnya Khalifah Usman bin Affan, yang telah menciptakan perang saudara yang disebut sebagai perang Unta (Jamal)[13]. Peperangan ini telah mengorbankan 6000 jiwa kaum Muslim[14]. Meski demikian menurut Buya peperangan ini belum lagi menghasilkan pertikaian teologis yang menyebabkan perpecahan kepada berbagai puak baik Suni, Syi’i, dan Khawarij. Tapi Buya meyakini bahwa pertikaian tersebut adalah pertikaian politik antar elite Arab saat itu dan bukanlah dipicu oleh pertikaian keagamaan apalagi pertikaian teologis.
Peristiwa pertikaian kedua terjadi pada perang Shiffin yang dipicu oleh ketidakpuasaan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan tehadap sikap Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menyikapi pembunuhan yang terjadi tehadap Khalifah Utsman sebelumnya. Muawiyah berasal dari Bani Umayah, sedangkan Ali bin Abi Thalib dari bahiHasyim. Keduanya sama-sama berasal dari suku Quraisy. Adapun Muawiyah merupakan satu marga dengan Utsman bin Affan.
Berdasarkan fakta di atas, Buya menyimpulkan bahwa pertikaian itu terjadi di kalangan elit Arab-Quraisy yang sebenarnya sama-sama memperebutkan kekuasaan. Maka dengan demikian patut disayangkan, karena pertikaian itu sebenarnya tidak perlu terjadi jika mereka benar-benar memegang pesan kuncidalam al-Qur’an mengenai persaudaraan dalam Islam.
Dengan adanya fenomena pertikaian diantara sesama muslim tersebut, Buya sampai pada kesimpulan bahwa persengketaan dan perpecahan di kalangan orang beriman adalah sebuah pengkhianatan tehadap al-Qur’an[15]. Dalam kalimat lain, peristiwa peperangan yang menimbulkan perpecahan tersebut adalah satu bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur perdamaian, rahmat, belas kasih, simpati, dan kebaikan yang diajarkan dalam Islam.[16]
Persengketaan politik setelah perang Shiffin itu bukan hanya berakibat buruk bagi persaudaraan Islam yang koyak pada saat itu. Tetapi lebih jauh dari itu, persengketaan tersebut membuahkan pertikaian abadi yang melahirkan perpecahan berbagai kelompok yang akarnya bisa ditelusuri pada tiga firqah besar: Suni, Syi’i dan Khawarij. Dari tiga firqah ini beranak pinak menjadi lebih dari 700 firqah, sebagaimana dijelaskan oleh Buya dengan mengutip pendapat Abdul Mun’im Hifni dalam kitabnya Mausu’ah al-Firaq wa al-Jama’at wa al-Madzahib al-Islamiyyah[17]. Induk dari semua firqah ini dapat ditelusuri pada tiga ekspresi di atas yang semula semuanya bercorak Arab.
Di banyak tulisan Buya berhenti melakukan analisis tentang biang kerok perpecahan umat dan tumbangnya moralitas persaudaraan dalam Islam dengan menunjuk jari pada peristiwa Shiffin ini. Karena melalui peristiwa tersebut lahir tiga faksi utama yang menjadi cikal bakal perpecahan berbagai kelompok dalam tubuh umat Islam.
Namun demikian, sepertinya Buya agak sedikit luput untuk menelaah lebih jauh akar yang lebih dalam mengapa terjadi perpecahan dan pecah kongsi dalam tubuh persaudaraan umat Islam periode awal. Seolah Buya tidak ingin beranjak menelusuri lebih jauh ke periode yang lebih dini dari peristiwa perang Jamal atau peristiwa Shiffin itu sendiri. Karena bagi sebagian sarjana Muslim dan beberapa sejarawan kritis seperti Muhammad Abid al-Jabiri, Khalil Abdul Karim, Hisham Jait, dan Ibrahim Baydhun, akar persoalan perpecahan umat Islam berawal dari tidak tuntasnya proses musyawarah pada peristiwa pertemuan di Saqifah Bani Saidah. Peristiwa tersebut bagi para intelektual di atas memiliki ekses yang tidak kecil dan dampaknya tidaklah singkat. Peristiwa pembai’atan tehadap Abu Bakar itu sendiri ditengarai terjadi melalui sebuah dialog yang dipaksakan. Dalam istilah Khalil Abdul Karim peristiwa Saqifah menghadirkan dialog dengan senjata (al-hiwar bi al-silah)[18].
 Ekses utama dari peristiwa Saqifah itu salah satunya bisa kita pertanyakan terkait posisi dan peran para sahabat dari kalangan Anshar dalam konstelasi politik umat pasca Rasul wafat terutama dalam masa-masa khilafah rasyidah. Nyaris kalau kita baca secara seksama, peran mereka sama sekali tidak menonjol, bahkan bisa dikatakan sangat nihil. Karena seolah keberadaan mereka telah tersingkirkan oleh deru dominasikekuasaan kaum Quraisy-Muhajirin. Seolah tidak ada ruang bagi kaum Anshar untuk berkiprah dalam entitas “Negara Madinah” pasca Rasul wafat. Bahkan dalam banyak riwayat, pemimpin kelompok Anshar yang benama Sa’ad bin Ubadah telah mengubah haluan politiknya menjadi seorang oposan bagi kekhilafahan rasyidah di Madinah dengan melakukan migrasi ke wilayah Syam/Suriah. Sampai-sampai dikisahkan, ia tidak mau lagi bermakmum dan berhaji bersama dua khalifah dari kaum Quraisy itu – Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar bin Khattab[19]. Ini menandakan persoalan kepemimpinan sejak Rasul wafat, bahkan sebelum jenazah beliau dimakamkan, telah menjadi faktor utama sengketa di kalangan kaum Muslimin. Dan lagi-lagi semua itu melibatkan kader-kader inti Nabi Muhammad SAW, baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar. Fakta kerasi ni agak jarang disebutkan dan dianalisis secara lebih mendalam oleh Buya.
Ekses utama dari peristiwa Saqifah itu salah satunya bisa kita pertanyakan terkait posisi dan peran para sahabat dari kalangan Anshar dalam konstelasi politik umat pasca Rasul wafat terutama dalam masa-masa khilafah rasyidah. Nyaris kalau kita baca secara seksama, peran mereka sama sekali tidak menonjol, bahkan bisa dikatakan sangat nihil. Karena seolah keberadaan mereka telah tersingkirkan oleh deru dominasikekuasaan kaum Quraisy-Muhajirin. Seolah tidak ada ruang bagi kaum Anshar untuk berkiprah dalam entitas “Negara Madinah” pasca Rasul wafat. Bahkan dalam banyak riwayat, pemimpin kelompok Anshar yang benama Sa’ad bin Ubadah telah mengubah haluan politiknya menjadi seorang oposan bagi kekhilafahan rasyidah di Madinah dengan melakukan migrasi ke wilayah Syam/Suriah. Sampai-sampai dikisahkan, ia tidak mau lagi bermakmum dan berhaji bersama dua khalifah dari kaum Quraisy itu – Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar bin Khattab[19]. Ini menandakan persoalan kepemimpinan sejak Rasul wafat, bahkan sebelum jenazah beliau dimakamkan, telah menjadi faktor utama sengketa di kalangan kaum Muslimin. Dan lagi-lagi semua itu melibatkan kader-kader inti Nabi Muhammad SAW, baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar. Fakta kerasi ni agak jarang disebutkan dan dianalisis secara lebih mendalam oleh Buya.
Kembali pada akar utama penyebab kemunduran dan krisis yang hinggap menyelimuti dunia Arab-Muslim. Dalam pandangan Buya, semua itu dikarenakan ego, kepentingan sesaat, dan hawa nafsu yang tak terkendali di kalangan sebagian umat, terutama di kalangan elitnya. Dalam sebuah tulisan Buya menyampaikan,
“Manakala ego, kepentingan, dan hawa nafsu mengalahkan kekuatan firman Allah, berarti kita telah berkhianat terhadap al-Qur’an, tetapi mengapa kita masih saja mengaku beriman kepada Kitab Suci ini? Tiga nilai buruk itu bisa saja dibungkus dalam selimut nasionalisme seperti yang sekarang berlaku antara Iran dan Saudi Arabia. Dalam kasus dua negara ini, yang dominan adalah sifat hegemonik, bukan karena perbedaan mazhab keagamaan”[20]
Tiga hal ini adalah faktor internal yang menyebabkan porak-poranda dan kehancuran yang mendera peradaban Arab-Muslim di berbagai belahan dunia. Bahkan dalam analisis lain, dengan mengutip pandangan Khaled Abou el-Fadl dan Mahmoud Khaled Mahmoud, Buya melihat ada faktor lain yang menjadi penyebab kegagalan kebangkitan dunia Islam di era kontemporer, terutama pasca era Musim Semi Arab pada tahun 2010 yang dimulai di Tunisia. Kegagalan tersebut diantaranya disebabkan oleh pertama, para pemimpinArab yang korup yang tidak mau kekuasaan dan kekayaan mereka terganggu dengan angin demokrasi yang dihembuskan Musim Semi Arab. Kedua, pemerintahan Barat yang rakus dan rasis yang cenderung mempertahankan status quo kondisi Arab yang relative dapat mereka tundukkan dan kendalikan.
Ketiga, kelompok “badut” (buffoons) yang angkuh yang mengklaim berbicara atas nama Islam. Kelompokbadut yang dimaksud Buya adalah kaum Islamis yang mewujud dalam bentuk kelompok radikal-teror seperti al-Qaeda, Jabhah Nusrah, ISIS, Boko Haram, dan sejenisnya. Mereka dalam pandangan Buya hanya sekedar pion yang diberi “kedok” Islam. Seolah-olah mereka benar-benar merepresentasikan ajaran Islam, umat Islam dan kepentingan Islam, padahal mereka hanyalah tukang manipulasi Islam untuk kepentinganpolitik-ekonomi kelompok mereka sendiri.
Tiga golongan ini diyakini telah menggagalkan upaya pembebasan dan kebebasan bangsa Arab dari tiranipenindasan, penghisapan, dan korupsi yang dilakukan oleh persekongkolan elit Arab dan pemerintahanbobrok Barat.[21] Hal ini ditambah dengan kegagapan umat Islam dari masa ke masa dalam membaca perilaku politik elit Muslim sejak awal hingga masa kontemporer telah menambah kegagalan yang sedang berlaku.
Persaudaraan Kemanusiaan yang Utuh dan Bulat
 Isu kemanusiaan adalah isu utama yang digeluti oleh Buya Syafii. Bagi Buya, kemanusiaan itu seharusnya hanya satu, utuh, bulat dan tidak lonjong, sebagaimana ia meyakini benar tentang konsep kemanusiaan al-Qur’an. Di dalam al-Qur’an ada beberapa ayat yang secara jelas memotret manusia dalam kemanusiaannya sebagai entitas (umat) yang tunggal (Kāna al-Nass Ummah Wahidah). Untuk mengafirmasi pandangan al-Qur’an tentang konsep kemanusiaan yang tunggal ini, Buya juga seringkali mengutip pandangan dan sikaptokoh perdamaian dunia asal India, Mahatma Gandhi yang menyatakan bahwa “all humanity is oneundivided and indivisible family, and each one of us is responsible for the misdeeds of the others”.[22] Oleh karena itu prinsip kemanusiaan harus dijadikan dasar dalam bersikap dan menghadapi berbagai persoalan di dunia ini, termasuk menjadi dasar dalam beragama. Kebinekaan dan keragaman umat manusia baik dari segi latarbelakang suku, agama, etnis, dan budaya tidak boleh menciptakan sebuah situasi perpecahan yang dapat meruntuhkan perumahan kemanusiaan semesta. Maka satu-satunya sikap dalam menghadapi keragaman dan perbedaan yang ada di dunia adalah menerimanya dengan sikap terbuka dan lapang dada penuh ketulusan.
Isu kemanusiaan adalah isu utama yang digeluti oleh Buya Syafii. Bagi Buya, kemanusiaan itu seharusnya hanya satu, utuh, bulat dan tidak lonjong, sebagaimana ia meyakini benar tentang konsep kemanusiaan al-Qur’an. Di dalam al-Qur’an ada beberapa ayat yang secara jelas memotret manusia dalam kemanusiaannya sebagai entitas (umat) yang tunggal (Kāna al-Nass Ummah Wahidah). Untuk mengafirmasi pandangan al-Qur’an tentang konsep kemanusiaan yang tunggal ini, Buya juga seringkali mengutip pandangan dan sikaptokoh perdamaian dunia asal India, Mahatma Gandhi yang menyatakan bahwa “all humanity is oneundivided and indivisible family, and each one of us is responsible for the misdeeds of the others”.[22] Oleh karena itu prinsip kemanusiaan harus dijadikan dasar dalam bersikap dan menghadapi berbagai persoalan di dunia ini, termasuk menjadi dasar dalam beragama. Kebinekaan dan keragaman umat manusia baik dari segi latarbelakang suku, agama, etnis, dan budaya tidak boleh menciptakan sebuah situasi perpecahan yang dapat meruntuhkan perumahan kemanusiaan semesta. Maka satu-satunya sikap dalam menghadapi keragaman dan perbedaan yang ada di dunia adalah menerimanya dengan sikap terbuka dan lapang dada penuh ketulusan.
Oleh karena itu dalam pandangan Buya, perspektif kemanusiaan dalam menyikapi perbedaan harus diperkuat oleh ikatan persaudaraan sesama umat manusia tanpa melihat ragam asal usul kelahiran, suku, agama, budaya, dan latar belakang primordialitas lainnya. Maka dalam hal ini, Buya menawarkan sebuah konsep persaudaraan kemanusiaan universal. Sejurus dengan itu, konsep persaudaraan kemanusiaan universal harus juga disokong oleh keadilan universal, sehingga dalam hubungan antar umat manusia, perdamaian dan harmoni tetap dapat dijaga.
Ketika membicarakan masalah kemanusiaan universal ini, Buya berdialog dengan al-Qur’an terutama melalui beragam penafsiran terhadap ayat-ayat yang mengandung pesan kemanusiaan universal. Salah satu yang dikaji adalah surat al-Hujurat ayat 10. Bagi Buya untuk meneguhkan kemanusiaan universal, berbagai kelompok umat manusia harus benar-benar mewujudkan persaudaraan sejati antar umat manusia. Dalam al-Qur’an, persaudaraan sejati ini didasarkan pada persaudaraan keimanan dan bahkan persaudaraan lintas iman yang berbeda.
Dalam sebuah tulisan ketika mengupas makna dari ayat tersebut, Buya menyatakan, “ikatan keturunan, latarbelakang sejarah, dan bangsa tidak boleh menghancurkan bangunan persaudaraan universal berdasarkanagama. Tetapi yang berlaku adalah sebaliknya: persaudaraan imaniah berantakan akibat perbedaan suku, bangsa, mazhab, dan latar belakang sejarah. Betapa jauhnya bangunan dunia Islam dari cita-cita mulia al-Qur’an.”
Bagi Buya, persaudaraan umat manusia yang didasari oleh keimanan adalah sebuah persaudaraan yang sejati, sebuah persaudaraan yang tidak lagi hanya diikat oleh ikatan keturunan, latar belakang sejarah, bangsa, suku, etnis, dan budaya. Namun dalam kenyataannya seringkali persaudaraan kemanusiaan yang didasarkan pada ikatan keimanan, hancur luluh-lantak juga oleh adanya sentiment kesukuan, etnis, dan budaya. Hal ini yang patut disesali ketika mengevaluasi perjalanan bangunan persaudaraan di antarasesama umat Islam baik pada masa-masa awal pembentukan Islam, maupun pada periode yang lebih kontemporer.
Ketika membahas pesan kunci tentang persaudaraan universal pada ayat 10 surat al- Hujurat ini, Buya mengutip terjemah al-Qur’an yang dilakukan oleh Abdullah Yusuf Ali, di dalamnya dikatakan, “Pelaksanaan/penguatan persaudaraan Muslim merupakan cita-cita sosial Islam yang terbesar. Atas dasar itulah Khutbah Nabi saat di haji wada’ disampaikan, dan Islam tidak mungkin diwujudkan dengan sempurna sampai cita-cita ini berhasil diraih)”[23]. Bagi Buya, Yusuf Ali telah menangkap dengan sempurna pesan historis dari ayat 10 ini”.[24]
Masa Depan Demokrasi dan Harapan pada Mentalitas Negarawan
 Sejak awal Buya membela demokrasi sebagai sebuah sistem yang ideal untuk diterapkan di manapun termasuk di Indonesia. Meskipun pembelaan itu dilakukan dengan catatan yang cukup panjang. Karena dalam kenyataannya, penerapan sistem demokrasi tidak selamanya berjalan dengan penuh harapan dan sesuai dengan cita-cita ideal sistem tersebut diterapkan. Dalam pengakuannya, Buya memang membela demokrasi dalam teori, tapi secara konsisten mengkritiknya dalam praktik[25]. Dalam pandangan Buya, seharusnya antara teori dan praktik demokrasi tidak ada kesenjangan yang tejadi.
Sejak awal Buya membela demokrasi sebagai sebuah sistem yang ideal untuk diterapkan di manapun termasuk di Indonesia. Meskipun pembelaan itu dilakukan dengan catatan yang cukup panjang. Karena dalam kenyataannya, penerapan sistem demokrasi tidak selamanya berjalan dengan penuh harapan dan sesuai dengan cita-cita ideal sistem tersebut diterapkan. Dalam pengakuannya, Buya memang membela demokrasi dalam teori, tapi secara konsisten mengkritiknya dalam praktik[25]. Dalam pandangan Buya, seharusnya antara teori dan praktik demokrasi tidak ada kesenjangan yang tejadi.
Dalam alam Indonesia merdeka, sejak awal demokrasi dijadikan sistem yang berlaku untuk menjalankankehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam perjalanannya, perkembangan demokrasi di Indonesia telah dirusak, dalam pandangan Buya, oleh para elitnya sendiri. Sepuluh tahun setelah kemerdekaan, negeri yang baru merangkak ini telah berhasil menyelenggarakan sebuah pemilihan umum yang berkualitas, jujur,adil, dan berwibawa pada tahun 1955. Hal ini dilakukan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap yang berasal dari partai Masyumi.
Bagi Buya keberhasilan Pemilu 1955 menjadi tonggak penting kehidupan demokrasi di Indonesia pasca-Kemerdekaan. Karena peristiwa politik tesebut menjadi penanda kemerdekaan dan kebebasan politik yang dimiliki oleh rakyat pasca sepuluh tahun merdeka. Namun usia kehidupan demokrasi atau prosesdemokratisasi tersebut harus terganggu dengan peristiwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan dibubarkannya Konstituante hasil Pemilu 1955, karena Konstituante dianggap gagal menetapkan undang-undang dasarterutama mengenai pasal dasar negara. Maka kekuasaan akhirnya dimonopoli oleh pemimpin tertinggidan menetapkan sistem Demokrasi Terpimpin 1959-1965. Proses ini jelas bagi Buya telah mencederai kehidupan demokrasi yang baru seumur jangung.
Demokrasi Terpimpin jelas merupakan sebuah sistem politik otoritarian yang telah memasung kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun yang juga lebih memprihatinkan setelah Demorasi Terpimpin tumbang dan digantikan dengan Demokrasi Pancasila ala Orde Baru, yang bukan hanya telah memasung, tapi malah telahmematikan demokrasi di Indonesia. Pembunuhan demokrasi ala Orde Baru dilakukan dengan mengatasnamakan Pancasila. Maka dalam istilah Buya, inilah yang disebut sebagai tragedi Pancasila, tragedi demokrasi selama tiga dasawarsa lebih.
Pancasila telah begitu indah diagungkan dalam kata dan kalimat, dalam pidato dan acara-acara resmi kenegaraan, namun senyatanya dikebiri dan dibungkam dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini Buya begitu sangat kritis ketika melihat kenyataan pahit semacam ini. Bahkan Buya menyebutnya sebagai pecah kongsi antara kata dan perbuatan dalam menggumuli Pancasila. Karena sejak awal Pancasila dirumuskan dengan kesaktian, namun selalu terkapar dalam realitas implementasi di lapangan.
Dalam kesaksian Buya, bahkan di antara lima sila Pancasila, ada satu sila yang telah menjadi yatim piatu, bahkan sejak kelima sila itu dilahirkan. Yakni sila ke-5 “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Ini artinya sila ini memang merupakan satu sila yang tak pernah diperhatikan dan dirawat oleh “ayah dan ibu kandung” yang telah melahirkannya serta “ayah-ibu sambung” yang seharusnya merawatnya. Sila yang sepertinya terlantar atau mungkin sengaja diterlantarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak lahir hingga saat ini.
Jikapun demokrasi mengalami pasang-surut dan timbul-tenggelam dalam kehidupan bangsa ini, sila keadilan sosial tetap absen dalam menemani hiruk pikuk kehidupan rakyat Indonesia. Demokrasi sejatinya harus memastikan dan menjamin keadilan dan kesejahteraan sosial dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat luas. Realitas demokrasi baik pada era Demokrasi Terpimpin (1959-1965) maupun pada era Demokrasi Pancasila (1966-1998), bukan hanya telah gagal menghadirkan keadilan sosial, tapi juga telah sama-sama memasung kebebasan dan kemerdekaan rakyat. Baru pada era Reformasi, kerana kebebasan itu telah dibuka seluasnya dalam batas-batas yang diharapkan, namun tetap gagal dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.
Ini tak lain menurut Buya karena kultur demokrasi kita masih belum matang dan ajeg. Demokrasi kita masih terlalu goyah jangankan untuk menghadirksan sebuah cita ideal keadilan sosial, bahkan untuk memastikan kebebasan itu berjalan, seringkali ruang demokrasi gagal untuk menghadirkannya. Bukan hanya karena pasungan struktural dari kekuatan negara yang cukup hegemonik, tapi juga pasungan itu juga seringkali hadir dari sesama warga bangsa yang merasa berada di atas angin mayoritas. Ini menjadi persoalan demokrasi kita.
Dalam angan Buya Syafii, untuk menghadirkan keadilan sosial, kultur demokrasi pada bangsa ini harus benar-benar diperkuat dengan menghadirkan sebanyak mungkin sosok- sosok negarawan yang memiliki visi yang jauh dan luas untuk kepentingan bangsa. Sebuah visi untuk sungguh-sungguh menghadirkan keadilan sosial melalui proses demokrasi. Bahkan bukan hanya menghadirkan sosok negarawan, tapi yang juga sangat penting adalah mewujudkan mentalitas negarawan di kalangan warga dengan semangat mau berkorban untuk kepentingan yang lebih luas dan berlapang dada terhadap perbedaan. Mentalitas negarawan adalah sebuah karakter yang pada dirinya “sudah selesai”. Dalam artian ia tidak lagi memikirkan kepentingan jangka pendek untuk dirinya dan kelompoknya. Seseorang yang betul-betul telah selesai dengan persoalan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Sehingga ia betul-betul memfokuskan diri dan energi positif yang dimilikinya untuk berkhidmat pada kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan umat dan manusia pada umumnya.
Sosok dan mentalitas negarawan seperti ini dapat memastikan umur demokrasi kita menjadi lebih panjang untuk diwujudkan dan dihidupkan dalam riak pergerakan berbangsa dan benegara. Satu pribadi yang seringdijadikan rujukan utama sosok dan mentalitas negarawan yang sejati dalam pandangan Buya Syafii adalah sosok Bung Hatta, sang proklamator Indonesia. Ia bukan hanya seorang yang demokratis secara nyata, tapi ia benar- benar seorang negarawan yang memikirkan kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Seorang yang menangguhkan urusan pernikahannya yang bersifat pribadi karena memikirkan kemerdekaan bangsa ini yang lebih fundamental. Pada sosok-sosok dan karakter yang dimiliki oleh seorang seperti Hatta lah Buya Syafii menaruh harapan dan optimisme agar bangsa ini bakal segera siuman dari berbagai krisis kehidupan yang menimpanya, termasuk krisis dalam kehidupan berdemokrasi. Sebagaimana optimisme Hatta sendiri terhadap realitas demokrasi di negeri ini, sebagaimana ungkapannya berikut:
“Pengakuan di muka Tuhan akan bepegang pada Pancasila itu tidak mudah diabaikan. Dan di situ pulalah teletak jaminan bahwa demokrasi tidak akan lenyap di Indonesia. Ia dapat tetekan sementara dengan bebagai rupa. Akan tetapi lenyap ia tidak. Lenyap demokrasi berarti lenyap Indonesia Merdeka”[26]
Penutup
 Artikel ini tidak berpretensi untuk menguraikan semua isu, tema, dan konsen yang selama ini telah digeluti oleh Buya Syafii Maarif. Buya sebagai seorang intelektual publik tentu memiliki kepekaan yang cukup tinggi terhadap berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, agama yang senantiasa menggelayuti kehidupan bangsa ini. Tapi kiranya mudah- mudahan tulisan ringan ini cukup untuk memotret pemikiran Buya Syafii berdasarkan pada perspektif keimanan/keislaman, keilmuan, dan kemanusiaan yang menjadikonsen dan perhatian Buya Syafii selama ini. Tentu ketiganya tidak luput untuk dilihat berdasarkan konteks Indonesia dan keindonesiaan yang menjadi tanah air dan identitas yang sangat Buya cintai secara tulus itu. Satu hal yang sering terngiang dari pesan fundamental yang sering Buya sampaikan tentang kecintaannya yang tulus pada tanah air ini adalah agar tanah air dan bangsa ini bisa bertahan dalam keutuhan dan persatuan sampai satu hari sebelum kiamat. Mari kita jaga asa dan cita Buya ini besama-sama!
Artikel ini tidak berpretensi untuk menguraikan semua isu, tema, dan konsen yang selama ini telah digeluti oleh Buya Syafii Maarif. Buya sebagai seorang intelektual publik tentu memiliki kepekaan yang cukup tinggi terhadap berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, agama yang senantiasa menggelayuti kehidupan bangsa ini. Tapi kiranya mudah- mudahan tulisan ringan ini cukup untuk memotret pemikiran Buya Syafii berdasarkan pada perspektif keimanan/keislaman, keilmuan, dan kemanusiaan yang menjadikonsen dan perhatian Buya Syafii selama ini. Tentu ketiganya tidak luput untuk dilihat berdasarkan konteks Indonesia dan keindonesiaan yang menjadi tanah air dan identitas yang sangat Buya cintai secara tulus itu. Satu hal yang sering terngiang dari pesan fundamental yang sering Buya sampaikan tentang kecintaannya yang tulus pada tanah air ini adalah agar tanah air dan bangsa ini bisa bertahan dalam keutuhan dan persatuan sampai satu hari sebelum kiamat. Mari kita jaga asa dan cita Buya ini besama-sama!
Nota akhir:
[1] M. Amin Abdullah, Buya Ahmad Syafii Maarif, Muslim Progresif, Fruitful Patriotism, dan Pembela Pancasila, Makalah disampaikan dalam Syafii Maarif Memorial Lecture, 5 Juli 2022, hal. 2
[2] Ahmad Syafii Maarif, Menggali Makam Ibu, Resonansi Republika, 19 Februari 2013. Lihat juga Ahmad Syafii Maarif, MemoarSeorang Anak Kampung, hal. 68
[3] Ahmad Syafii Maarif, Memoar Si Anak Kampung, hal. 184
[4] Maarif, Memoar Si Anak Kampung, hal. 82
[5] Maarif, Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, 1995, hal 202
[6] Maarif, Memoar Si Anak Kampung, hal 61
[7] Mun’im Sirry, ‘Ahmad Syafii Maarif dan Rekonfigurasi Pembacaan al-Quran’, dalam Darraz, dkk (eds.), Muazin Bangsa dari MakkahDarat, hal. 56
[8] Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, bandung: Mizan, 2015, hal. 318-319
[9] Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, hal. 278
[10] Pertemuan terbatas ini diadakan di sebuah tempat di Jakarta yang difasilitasi oleh Leimena Institute pada 6 Desember 2017. Di antara yang hadir selain Buya adalah Prof. Dr. M. Quraish Shihab, Prof. M. Amin Abdullah, Prof. Dr. Alwi Shihab, Kyai Shalahuddin Wahid, Kyai Masdar Farid Mas’udi, Prof. Mun’im Sirry, Ph.D., Dr. Jacob Tobing, Matius Ho, Ph.D., dan beberapa lainnya termasukpenulis sendiri yang hadir dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri perdebatan tersebut.
[11] Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, hal. 15
[12] Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, hal. 17
[13] Maarif, Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam, hal. 3, 15
[14] Maarif, Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam, hal. 4
[15] Maarif, Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam, hal. 29
[16] Maarif, Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam, hal. 41
[17] Lihat Abdul Mun’im Hifni dalam kitabnya Mausu’ah al-Firaq wa al-Jama’at wa al-Madzahib al- Islamiyyah, Kairo: Dar al-Rasyad, 1993; Lihat Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, hal. 192
[18] Khalil Abdul Karim, al-Judzur al-Tarikhiyyah li al-Syari’ah al-Islamiyyah, Kairo: Sina li al-Nasyr, 1990, hal. 110; lihat juga M. Abdullah Darraz, Khilafah, Bay’ah dan Pembentukan Otoritas Politik-Keagamaan dalam Islam, dalam M. Abdullah Darraz (ed.), Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah, dan Terorisme, Bandung: Mizan, 2017, hal. 515
[19] Baca ulasan mengenai hal ini pada tautan berikut: https://geotimes.id/kolom/saad-bin-ubadah-dan- absennya-politik-representasi-dalam-khilafah-rasyidah-bagian-1/ dan https://geotimes.id/kolom/saad-bin-ubadah-dan-absennya-politik-representasi-dalam-khilafah-rasyidah-bagian-2/
[20] Maarif, Al-Quran, Umat Islam, dan Persaudaraan Universal, Resonansi 13 Januari 2015
[21] Maarif, Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam, hal. 158
[22] Lihat Ahmad Syafii Maarif, Persaudaraan Sejati Umat Manusia: Perspektif Seorang Muslim, Makalah disampaikan pada Kongres Persaudaraan Sejati Lintas Iman, bertempat di Kompleks Museum Misi Muntilan, Jl. R.A. Kartini No. 3, pada 24-25 Oktober 2014
[23] Maarif, Al-Quran, Umat Islam, dan Persaudaraan Universal, Resonansi 20 Januari 2015; lihat juga Maarif, Krisis Arab dan MasaDepan Dunia Islam, hal. 139-140
[24] Maarif, Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam, hal. 140
[25] Maarif, Islam dalam Bingkai KeIndonesiaan dan Kemanusiaan, hal. 145
[26] Hatta, Demokrasi Kita, Jakarta: Pustaka Antara, 1966, hal. 30; Lihat juga Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, hal. 162-163.
 Muhammad Abdulah Darraz adalah Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau juga adalah aktivis Intelektual Muda Muhammadiyah, dan Direktur Eksekutif di MAARIF Institute for Culture and Humanity periode 2017-2019. Ucapan ini disampaikan dalam Workshop Ilmiah Forum Mahasiswa PAscasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Sabtu 16 Juli 2022 dengan tema: “Guru Bangsa dan Politik Indonesia: Analisis Pemikiran Gusdur dan Buya Syafii Maarif, Menyongsong Politik Indonesia di Masa Depan”.
Muhammad Abdulah Darraz adalah Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau juga adalah aktivis Intelektual Muda Muhammadiyah, dan Direktur Eksekutif di MAARIF Institute for Culture and Humanity periode 2017-2019. Ucapan ini disampaikan dalam Workshop Ilmiah Forum Mahasiswa PAscasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Sabtu 16 Juli 2022 dengan tema: “Guru Bangsa dan Politik Indonesia: Analisis Pemikiran Gusdur dan Buya Syafii Maarif, Menyongsong Politik Indonesia di Masa Depan”.